Kisah Hukum Perdata: Warisan Kolonial di Jantung Hukum Modern Indonesia
PERDATA
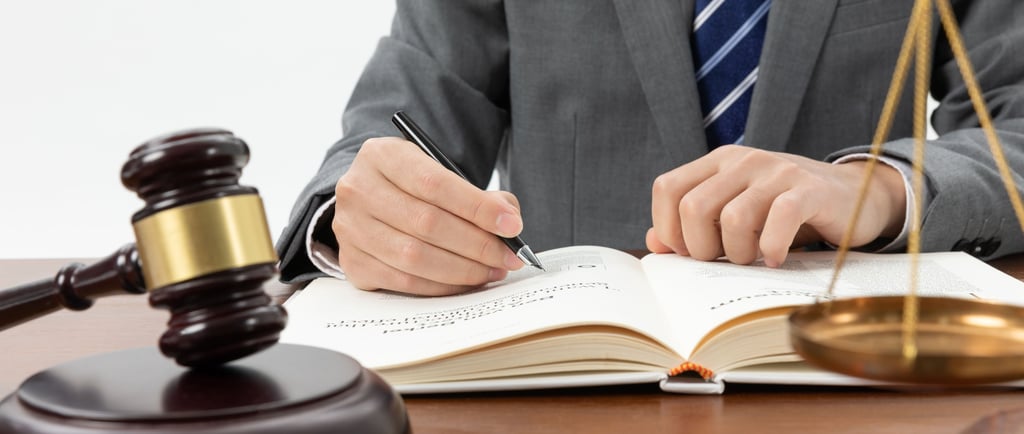

Di dalam sistem hukum Indonesia, terdapat sebuah produk hukum fundamental yang usianya lebih dari 170 tahun, namun pengaruhnya masih terasa kuat hingga hari ini. Inilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sebuah warisan dari era kolonial Belanda yang posisinya unik: sebagian besar isinya telah usang, namun beberapa bagian intinya justru menjadi penopang utama aktivitas ekonomi modern. Ini adalah kisah perjalanannya yang kompleks.
Babak 1: Bermula dari Eropa, Diberlakukan di Hindia Belanda
Kisah KUHPerdata dimulai di Eropa pasca-Revolusi Prancis. Inspirasi utamanya adalah Code Napoléon (1804), sebuah kodifikasi hukum yang menyebar ke seluruh benua, termasuk Belanda. Belanda kemudian membuat kodifikasi hukum perdatanya sendiri, Burgerlijk Wetboek (BW), pada tahun 1838.
Bagaimana aturan ini bisa sampai ke Indonesia? Jawabannya adalah asas konkordansi. Ini adalah prinsip politik hukum kolonial yang mengharuskan hukum bagi golongan Eropa di tanah jajahan sama dengan hukum yang berlaku di Belanda. Tujuannya jelas: menjamin kepastian hukum dan kelancaran roda bisnis mereka. Maka, pada 1 Mei 1848, Burgerlijk Wetboek resmi diberlakukan di Hindia Belanda.
Babak 2: Hukum Sebagai Alat Politik Pluralisme
Pemerintah kolonial tidak memberlakukan KUHPerdata untuk semua penduduk. Sebaliknya, hukum dijadikan instrumen untuk melanggengkan perbedaan sosial melalui politik hukum pluralisme. Berdasarkan Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS), penduduk dibagi menjadi tiga golongan dengan sistem hukum yang berbeda:
Golongan Eropa: Menjalankan KUHPerdata secara penuh.
Golongan Timur Asing (Tionghoa, Arab, India): Menjalankan KUHPerdata dengan beberapa pengecualian.
Golongan Pribumi (Inlanders): Tetap menggunakan hukum adat mereka.
Pembedaan ini menciptakan sekat-sekat hukum di masyarakat. Aturan tentang perkawinan, waris, hingga hak atas tanah berbeda untuk setiap golongan. Kebijakan ini secara efektif mempertahankan fragmentasi sosial dan menghambat terbentuknya identitas hukum yang tunggal.
Babak 3: Era Kemerdekaan dan Pembangunan Hukum Nasional
Setelah Proklamasi 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk membangun sistem hukum nasionalnya sendiri. Namun, proses ini tidak terjadi seketika. Melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, peraturan kolonial seperti KUHPerdata tetap berlaku untuk mencegah kekosongan hukum.
Sejak saat itu, dimulailah proses dekolonisasi hukum. Pemerintah secara bertahap mengganti bagian-bagian KUHPerdata yang tidak lagi sesuai dengan nilai dan kebutuhan bangsa melalui undang-undang baru.
Reformasi Hukum Keluarga (1974): UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hadir untuk menciptakan unifikasi hukum. UU ini mengubah secara mendasar filosofi perkawinan dari sekadar "hubungan perdata" menjadi "ikatan lahir batin" berdasarkan Ketuhanan. Prinsip kesetaraan suami-istri ditegakkan, sekaligus menghapus pasal-pasal dalam KUHPerdata yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.
Reformasi Hukum Tanah (1960): UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi tonggak sejarah. UU ini secara tegas mencabut Buku II KUHPerdata yang mengatur tentang tanah. Konsep hak tanah Barat seperti eigendom diganti dengan sistem hak atas tanah nasional yang berakar pada hukum adat, seperti Hak Milik, HGU, dan HGB.
Modernisasi Hukum Jaminan (1996 & 1999): Untuk menjawab kebutuhan dunia usaha modern, dibentuklah UU Hak Tanggungan (1996) yang menggantikan hipotek atas tanah, serta UU Jaminan Fidusia (1999) yang menyediakan mekanisme jaminan yang lebih fleksibel untuk benda-benda bergerak.
Babak 4: Bagian yang Bertahan dan Tetap Relevan
Meski sebagian besar isinya telah digantikan, KUHPerdata tidak sepenuhnya tidak berlaku. Satu bagian terpentingnya masih sangat relevan hingga kini: Buku III tentang Perikatan.
Bagian ini memuat prinsip-prinsip universal hukum kontrak yang menjadi fondasi seluruh aktivitas ekonomi, seperti:
Asas Kebebasan Berkontrak: Memberi keleluasaan bagi siapa saja untuk membuat perjanjian.
Asas Konsensualisme: Perjanjian sah sejak adanya kata sepakat.
Asas Itikad Baik: Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan jujur.
Prinsip-prinsip inilah yang bekerja setiap kali kita melakukan transaksi jual-beli, menandatangani kontrak kerja, mengajukan pinjaman, atau bahkan berbelanja online. Buku III KUHPerdata berfungsi sebagai lex generalis (hukum umum) yang menjadi rujukan utama dalam hukum bisnis dan perdata di Indonesia.
Epilog: Warisan yang Menanti Pembaruan
KUHPerdata saat ini memiliki status yang paradoksal. Sebagian besar isinya adalah arsip sejarah, sementara bagian lainnya menjadi tulang punggung hukum ekonomi modern. Kondisi ini menunjukkan sebuah perjalanan panjang sebuah bangsa dalam membangun sistem hukumnya sendiri—melepaskan diri dari warisan kolonial sambil tetap memanfaatkan prinsip-prinsip hukum yang terbukti universal.
Kisah ini masih berlanjut. Upaya untuk merumuskan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional yang komprehensif, modern, dan sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai bangsa terus berjalan. Kehadirannya kelak akan menjadi penanda final dari kemandirian hukum Indonesia di abad ke-21.


